
Oleh Asrudin Azwar
Setelah sekian kali menonton film Hannah Arendt (2012, download film), filsuf Yahudi dan teoretikus politik jenius yang menjadi tersohor karena salah satu bukunya yang paling berpengaruh di abad 20 dan begitu saya kagumi, The Origins of Totalitarianism (1951), akhirnya saya tergerak untuk menuliskannya.
Film itu bertemakan biografi: mengupas Arendt, mulai dari yang ringan (kehidupan rumahtangganya) hingga sampai ke persoalan yang berat (politik). Namun bukan persoalan ringan itu yang ingin dikupas dalam tulisan ini, melainkan pembelaan Arendt atas Adolf Eichmann. Sebagaimana diketahui pada 1961, Arendt bersama Majalah The New Yorker pergi ke Yerusalem untuk meliput pengadilan atas Adolf Eichmann, birokrat Nazi yang didakwa mengarahkan pengiriman orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi dalam Perang Dunia II. Liputan (artikel) itu kemudian diperluas dan diterbitkan menjadi buku pada 1963 dengan judul Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.
Dalam liputannya itu, Arendt mengamati bahwa pada dasarnya Eichmann tidak punya motif apa pun untuk membunuh Yahudi. Hannah menemukan fakta bahwa Eichmaan bukanlah seorang anti-Semitis. Dia tidak pernah membenci apalagi membunuh seseorang karena keyahudian-nya. Alasan Eichmann untuk “merestui” pembunuhan massal itu murni alasan birokratis. Dia melakukan itu karena hukum memerintahkan demikian dan peraturan yang berlaku ketika itu.
Arendt juga menyebutkan, Eichmann adalah pejabat biasa-biasa saja dan bukan monster sadis seperti yang banyak orang ingin bayangkan. Bagi Arendt, orang tidak akan bisa membuktikan adanya setan atau iblis apa pun dari diri Eichmann. Kejahatannya tidak radikal, tetapi banal (dangkal atau biasa-biasa saja). Eichmann melakukan itu karena ia taat pada aturan hukum yang kemudian memicu pembunuhan atas jutaan orang Yahudi. Hal itu dinilai Arendt tidak bisa dijadikan motif. Menurut Arendt, aturan hukum itu yang telah membuat Eichmann tidak lagi bisa berpikir. Karena dia tidak bisa berpikir, maka Eichmann tidak bisa melakukan penilaian moral atas tindakannya sendiri. Dengan begitu, tindakan Eichmann, Arendt menegaskan, bukanlah sebuah kesalahan.
Di sini terlihat sekali metode berpikir Heideggerian dalam diri Arendt. Martin Heidegger adalah pacar gelap sekaligus mentor filsafat Arendt di Universitas Marburg. Kata Heidegger, “Berpikir tidak menghasilkan apa-apa. Berpikir tidak bisa membuat kita bergerak. Apa yang membuat kita bergerak adalah kehidupan itu sendiri.”
Itu artinya Eichmann tidak berpikir. Dia hanya bergerak. Dia digerakkan oleh aturan hukum dan aturan itu disebut sebagai ideologi. Ideologi yang memaksa Eichmann untuk bertindak. Kesimpulannya, kata Arendt, Eichman adalah korban ideologi dan membuat dirinya menjadi terjerumus dalam pembunuhan massal.
Padahal kalau melihat kiprahnya pada 1930-an, Arendt begitu aktif dalam politik kaum Yahudi lantaran merebaknya politik anti-semitisme dan ideologi Nazisme yang hampir menguasai seluruh kehidupan Jerman. Dalam aktivitas politiknya itu, Arendt bekerja untuk Organisasi Zionis Jerman yang memublikasikan apa yang disebut sebagai kejahatan terhadap orang Yahudi. Bahkan ia sempat ditahan karena pekerjaannya itu. Ia lalu kabur dari Jerman menuju Paris tanpa dokumen sehingga menjadi orang Yahudi yang stateless (tanpa negara).
Jika melihat perjuangan politiknya itu untuk kaum Yahudi, Arendt terlihat menjadi begitu ambivalen karena pembelaannya atas Eichmann. Tak pelak, pembelaannya itu menghasilkan banyak kecaman keras dari kaum Yahudi maupun orang tertentu yang mempunyai kepentingan tertentu. Tak cuma kecaman, Arendt pun harus rela kehilangan banyak teman, dan hubungannya dengan komunitas Yahudi yang terorganisasi secara efektif menjadi terputus (Patricia Owens, 2009).
Itulah sebab mengapa saya menilai metode berpikir Arendt ala Heideggerian ini lugu. Hanya karena alasan digerakkan ideologi, manusia dinilainya bisa bebas dari kesalahan. Manusia berpikir semestinya menuntut manusia itu menjadi bisa memilah mana benar dan mana salah. Jika memang ada aturan (ideologi) yang memaksa ia ikut dalam rencana pembunuhan masal, semestinya ia menolak itu atas dasar kemanusiaan, walaupun hal itu akan mengancam nyawanya sendiri. Mesti diingat bahwa manusia berpikir jugu dituntut memiliki etika. Tujuannya adalah agar manusia memiliki tanggungjawab terhadap manusia lainnya (the other). Kalau kata filsuf kelahiran Lithuania Emmanuel Levinas, ini yang sebut sebagai tanggungjawab etika.
Karenanya menjadi tak heran jika suatu hari Hans J. Morgenthau pernah mengomentari buku Eichmann in Jerusalem. Menurutnya buku ini disusun untuk menggerakkan pemikiran kita dan menganggu hati nurani kita. Bahkan buat saya buku ini malah bisa merusak hati nurani kita. Sekali lagi, Arendt boleh jadi merupakan seorang filsuf dan teoretikus politik yang jenius, tetapi pembelaannya yang membabi buta atas Eichmann hanya akan membuat dirinya layak dicap sebagai filsuf yang lugu.
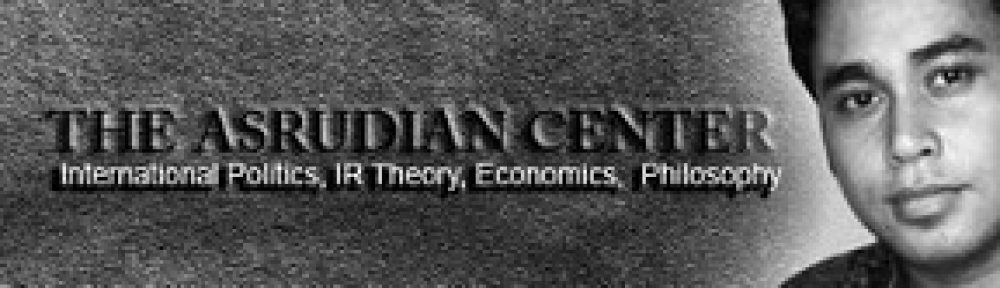
Reblogged this on Insan Cendekia.
Trims, Ali Aziz. Semoga bermanfaat 🙂